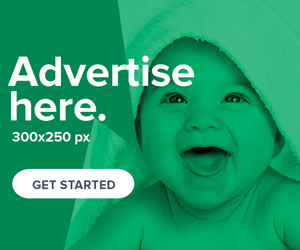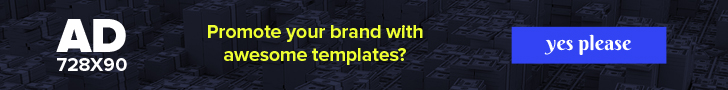Tujuh Teknik Bertanya yang Hancurkan Logika Lemah
Orang lebih sering merasa yakin karena bisa berbicara panjang, bukan karena argumennya benar. Itulah mengapa pertanyaan yang tajam jauh lebih mematikan daripada jawaban panjang yang berputar-putar. Menariknya, penelitian dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa orang yang pandai bertanya justru terlihat lebih cerdas dibanding mereka yang hanya pandai menjawab. Pertanyaan bukan sekadar alat klarifikasi, tetapi senjata untuk menguji konsistensi berpikir.
Kita semua pasti pernah berada dalam situasi debat sehari-hari, entah saat diskusi di kantor, ngobrol di warung kopi, atau bahkan ketika membaca argumen ngawur di media sosial. Banyak orang yang mengira suara keras dan kalimat panjang otomatis membuat mereka benar. Padahal, satu pertanyaan kritis saja bisa meruntuhkan fondasi logika yang rapuh. Dari sinilah pentingnya mempelajari teknik bertanya, bukan sekadar teknik menjawab.
Berikut tujuh teknik bertanya yang diuraikan berdasarkan buku-buku kredibel seperti The Socratic Method (Ward Farnsworth), Thank You for Arguing (Jay Heinrichs), Critical Thinking (Richard Paul & Linda Elder), Asking the Right Questions (Neil Browne & Stuart Keeley), Logic Made Easy (Deborah Bennett), The Art of Thinking Clearly (Rolf Dobelli), dan How to Win Every Argument (Madsen Pirie).
1. Pertanyaan Definisi
Dalam The Socratic Method, Ward Farnsworth menjelaskan bahwa hampir semua perdebatan runtuh di titik definisi. Misalnya, saat seseorang berkata “kebebasan itu mutlak,” maka pertanyaan sederhana adalah “Apa yang Anda maksud dengan kebebasan?” Pertanyaan ini memaksa lawan bicara untuk berhenti berselancar di kata besar dan kembali ke fondasi makna.
Contoh nyatanya terjadi dalam diskusi politik. Banyak orang mengklaim “demokrasi” tanpa bisa menjelaskan bentuk demokrasi seperti apa yang mereka maksud. Ketika ditanya definisinya, mereka sering kebingungan atau terjebak pada pengertian yang kabur. Inilah momen di mana logika lemah terbongkar dengan sendirinya.
Membiasakan diri bertanya tentang definisi adalah cara tercepat untuk menyingkap kabut retorika. Definisi adalah titik pijak berpikir, dan tanpa itu argumen hanya sekadar jargon kosong.
2. Pertanyaan Konsistensi
Neil Browne dalam Asking the Right Questions menekankan pentingnya bertanya: “Apakah argumen ini konsisten dengan argumen lain yang Anda buat sebelumnya?” Pertanyaan konsistensi membongkar kontradiksi yang sering luput dari kesadaran pembicara.
Misalnya seseorang mengkritik pemerintah karena menaikkan pajak, tetapi di sisi lain menuntut fasilitas publik yang lebih lengkap. Pertanyaan konsistensi akan menunjukkan adanya ketidakselarasan antara keinginan dan logika. Dari sini terlihat bahwa banyak argumen runtuh bukan karena serangan frontal, tetapi karena ditabrakkan pada pernyataan mereka sendiri.
Di sinilah kekuatan pertanyaan konsistensi, ia bekerja seperti cermin. Membuat orang melihat dirinya sendiri sering lebih memalukan daripada dikritik orang lain.
3. Pertanyaan Bukti
Richard Paul dalam Critical Thinking menegaskan bahwa argumen tanpa bukti hanyalah opini. Pertanyaan sederhana seperti “Apa buktinya?” sudah cukup untuk menguji validitas klaim.
Di media sosial, sering kita menemukan pernyataan seperti “Anak muda sekarang malas membaca.” Begitu ditanya bukti apa yang mendukung klaim itu, biasanya jawabannya samar: “Ya lihat saja di sekitar.” Tanpa data, argumen hanya berbentuk asumsi.
Mengajukan pertanyaan bukti membuat diskusi lebih sehat. Alih-alih bertengkar dengan opini melayang, kita memaksa percakapan kembali ke kenyataan yang bisa diverifikasi.
4. Pertanyaan Konsekuensi
Dalam Logic Made Easy, Deborah Bennett menyebut pentingnya bertanya: “Kalau pendapat itu diikuti, konsekuensinya apa?” Pertanyaan ini memaksa orang berpikir melampaui klaim dan melihat dampaknya.
Contoh konkret: ketika seseorang berkata “sebaiknya semua orang bekerja dari rumah saja,” maka pertanyaan konsekuensi adalah “Apakah semua jenis pekerjaan bisa dikerjakan dari rumah? Bagaimana dengan petani, tukang bangunan, atau sopir?” Dengan cara ini, argumen yang awalnya terdengar ideal terbukti tidak realistis.
Pertanyaan konsekuensi sangat efektif membongkar logika lemah yang lahir dari keinginan utopis tanpa memikirkan realitas kompleks.
5. Pertanyaan Sumber
Jay Heinrichs dalam Thank You for Arguing menyinggung betapa pentingnya otoritas sumber. Pertanyaan “Darimana sumber Anda?” bisa menghancurkan argumen yang hanya berdiri di atas gosip atau opini pribadi.
Misalnya dalam percakapan sehari-hari, orang sering berkata “Katanya dokter A menyarankan ini.” Begitu diminta menyebutkan nama, jurnal, atau bukti nyata, biasanya klaim itu ambruk. Pertanyaan ini bukan soal meremehkan, tetapi menuntut tanggung jawab intelektual dari siapa pun yang mengajukan argumen.
Tanpa kebiasaan menanyakan sumber, kita hanya akan hidup dalam banjir klaim yang tidak jelas asalnya.
6. Pertanyaan Alternatif
Rolf Dobelli dalam The Art of Thinking Clearly menyinggung bias yang membuat orang hanya melihat satu pilihan. Pertanyaan “Apakah ada alternatif lain?” sering kali membuat argumen tunggal tampak kerdil.
Misalnya, ketika seseorang mengatakan “Satu-satunya solusi untuk masalah ekonomi adalah menaikkan upah,” pertanyaan alternatif memaksa untuk melihat opsi lain: reformasi pajak, perbaikan distribusi, atau efisiensi birokrasi. Dengan membuka ruang alternatif, logika lemah yang kaku bisa segera dipatahkan.
Pertanyaan alternatif memberi kita kebebasan intelektual. Ia mengajarkan bahwa dalam hampir semua persoalan, tidak ada jalan tunggal.
7. Pertanyaan Intensi
Madsen Pirie dalam How to Win Every Argument menyoroti betapa seringnya orang menyembunyikan motif di balik argumen. Pertanyaan seperti “Mengapa Anda mendorong argumen ini? Apa yang ingin dicapai?” bisa mengungkap bias dan kepentingan tersembunyi.
Contohnya terlihat dalam debat produk kesehatan di televisi. Seseorang bisa mempromosikan gaya hidup sehat, tetapi ternyata motif utamanya adalah menjual produk herbal tertentu. Begitu ditanya intensinya, klaim “ilmiah” mereka runtuh menjadi strategi pemasaran.
Pertanyaan intensi bukan sekadar membongkar argumen, tetapi juga membuka ruang kejujuran. Saat motif disadari, diskusi berubah lebih jernih dan rasional.
Di titik ini, bertanya bukan lagi sekadar mencari jawaban, melainkan membentuk disiplin berpikir kritis. Kalau ingin konten eksklusif lain tentang cara mengasah logika dan menghancurkan sesat pikir populer, berlangganan di logikafilsuf.
Jadi, pertanyaannya sederhana: teknik bertanya mana yang paling sering kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa bagikan tulisan ini agar lebih banyak orang sadar bahwa logika lemah bisa runtuh hanya dengan satu pertanyaan tajam.#ES
Direferensi dari media sosial..