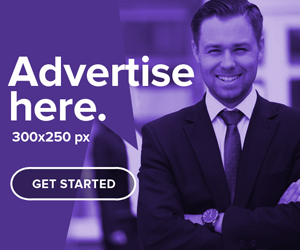Oleh : Dr. Bahrodin
Apakah benar orang yang menang berdebat adalah mereka yang paling keras suaranya? Banyak orang masih percaya bahwa semakin tinggi nada, semakin kuat argumen terdengar. Padahal, dalam ilmu retorika klasik maupun psikologi modern, suara yang meninggi sering kali justru tanda kelemahan dalam mengendalikan diri.
Fakta menariknya, menurut Daniel Goleman dalam Emotional Intelligence (1995), lebih dari 80 persen kualitas komunikasi ditentukan oleh kemampuan mengelola emosi, bukan sekadar kepintaran logika. Ini artinya, kendali diri dalam perdebatan lebih menentukan siapa yang benar-benar unggul, bukan seberapa tajam kata-kata yang dilontarkan.
Kita semua pernah terjebak dalam perdebatan kecil sehari-hari. Entah saat rapat kerja, diskusi kelas, atau bahkan sekadar perdebatan di meja makan keluarga. Sering kali bukan substansi argumen yang memperburuk keadaan, melainkan cara kita gagal menjaga ketenangan. Di sinilah seni menahan emosi menjadi keterampilan yang lebih penting dari sekadar kumpulan fakta.
1. Mengenali pemicu emosimu
Dalam buku The Chimp Paradox karya Steve Peters (2012), dijelaskan bahwa otak manusia memiliki “chimp brain” atau bagian emosional yang lebih reaktif daripada rasionalitas. Saat berdebat, “chimp” inilah yang cepat tersulut, memaksa kita berbicara tanpa berpikir. Dengan mengenali pemicu—seperti nada suara lawan bicara, pilihan kata, atau bahkan gestur—kita lebih mudah memberi jeda pada respons.
Misalnya, dalam sebuah rapat, seseorang menyela argumenmu dengan nada meremehkan. Secara instingtif, marah mudah muncul. Namun, dengan sadar mengenali bahwa rasa tersinggung adalah pemicu, kamu bisa menunda reaksi. Sejenak menarik napas atau meneguk air putih sering kali lebih ampuh daripada membalas dengan kata kasar.
Mengendalikan emosi bukan soal menekan, melainkan mengarahkan. Sama halnya seperti menahan air di bendungan, semakin kuat aliran dikontrol, semakin besar daya yang bisa dimanfaatkan.
2. Menunda respons sejenak
Victor Frankl dalam Man’s Search for Meaning (1946) menekankan bahwa ada ruang kecil antara stimulus dan respons, dan di ruang itulah kebebasan manusia berdiam. Dalam perdebatan, ruang ini sering kali hanya beberapa detik, tapi cukup menentukan arah pembicaraan.
Saat seseorang menyerang argumenmu, bukannya langsung menyahut, memberi jeda sejenak akan membuat lawan bicara justru merasa tidak berkuasa atas emosimu. Diam lima detik bisa terasa lama, tetapi jeda ini memberi waktu otak rasional untuk mengambil alih dari otak emosional.
Kebiasaan menunda respons juga memberi kesan wibawa. Orang lain akan melihatmu sebagai sosok yang matang, bukan reaktif. Inilah cara sederhana tetapi efektif untuk menjaga marwah dalam diskusi.
3. Mengubah nada suara
Chris Voss, mantan negosiator FBI dalam bukunya Never Split the Difference (2016), menyebut teknik “late-night FM DJ voice” sebagai salah satu cara menurunkan ketegangan. Nada suara rendah, tenang, dan stabil lebih memengaruhi suasana batin lawan bicara daripada argumen panjang sekalipun.
Misalnya, ketika teman debatmu mulai meninggikan suara, kamu justru menurunkan nada bicara. Kontras ini sering kali membuat lawan menyesuaikan diri, karena manusia cenderung meniru ritme percakapan yang ia hadapi.
Di sinilah seni retorika bekerja: bukan hanya isi kata-kata, tetapi juga musiknya. Ketika nada suara terkendali, emosi pun lebih mudah dijinakkan.
4. Memisahkan orang dari masalah
Roger Fisher dan William Ury dalam Getting to Yes (1981) menegaskan bahwa dalam setiap konflik, penting memisahkan orang dari masalah. Banyak perdebatan gagal produktif karena lawan dianggap sebagai musuh, bukan rekan diskusi yang membawa perspektif berbeda.
Misalnya, ketika seorang kolega menolak ide presentasimu, sering kali kita melihatnya sebagai serangan pribadi. Padahal, ia mungkin hanya menilai dari sisi efisiensi atau keterbatasan anggaran. Dengan memisahkan pribadi dari argumen, kamu tidak akan mudah terbawa emosi.
Pendekatan ini mengubah perdebatan dari arena adu ego menjadi forum kolaborasi. Dalam kerangka itu, emosi lebih mudah dikelola karena fokus kita bukan lagi pada siapa yang kalah-menang, melainkan bagaimana mencari kebenaran bersama.
5. Menggunakan humor seperlunya
Dalam Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic (Henri Bergson, 1900), humor dipandang sebagai mekanisme sosial untuk meredakan ketegangan. Menyisipkan humor ringan saat perdebatan bisa mengubah suasana menjadi lebih cair tanpa kehilangan substansi argumen.
Contohnya, saat debat memanas soal topik serius, melempar komentar santai seperti, “Kalau kita terus begini, kopi saya keburu dingin,” dapat menurunkan intensitas. Namun, humor harus digunakan dengan cermat agar tidak terkesan meremehkan lawan.
Di tengah penjelasan seperti ini, banyak orang menyadari bahwa keterampilan berargumen sejatinya bisa terus diasah. Justru di sinilah pentingnya mengakses pembahasan yang lebih mendalam di logikafilsuf, tempat di mana retorika dan filsafat disajikan lebih eksklusif untuk memperkaya cara kita berpikir.
6. Menarik napas dalam-dalam
Andrew Weil dalam Breathing: The Master Key to Self-Healing (1999) menunjukkan bahwa pola napas berpengaruh langsung pada emosi. Napas dangkal mempercepat rasa cemas dan marah, sementara napas panjang dan dalam menurunkan ketegangan saraf.
Dalam praktik sehari-hari, sebelum menanggapi argumen yang menekan, menunda dengan menarik napas dalam beberapa kali sering membuat respons lebih terkendali. Teknik sederhana ini seolah memberi jeda alami pada tubuh sebelum akal mengambil alih.
Di ruang debat, orang yang terlihat tenang dengan ritme napas teratur sering lebih dihormati ketimbang yang cepat tersulut. Menguasai napas berarti menguasai diri.
7. Mengingat tujuan berdebat
Dalam Thank You for Arguing karya Jay Heinrichs (2007), ditegaskan bahwa berdebat bukanlah tentang menjatuhkan lawan, melainkan membujuk audiens atau mencapai pemahaman bersama. Mengingat tujuan ini membantu menjaga agar emosi tidak melampaui akal sehat.
Ketika emosi mulai menguasai, tanyakan pada diri sendiri: apa sebenarnya yang ingin dicapai? Apakah sekadar melampiaskan ego atau memperkuat argumen agar lebih bisa diterima? Kesadaran ini menjadi rem alami bagi ledakan emosional.
Debat sejatinya bukan arena gladiator, melainkan ruang dialektika. Orang yang sadar akan tujuan besarnya, cenderung lebih tenang dan tidak mudah terbakar.
Menahan emosi dalam perdebatan bukan berarti mematikan perasaan, melainkan mengendalikannya agar akal tetap jernih. Dengan menguasai seni ini, kita tidak hanya memenangkan argumen, tetapi juga menjaga martabat diri. Menurutmu, cara mana yang paling sulit dilakukan saat berdebat: menahan diri untuk diam atau menurunkan nada suara? Bagikan pendapatmu dan jangan lupa share agar lebih banyak orang belajar seni mengendalikan emosi.#ES
Direfensi dari Media Sosial
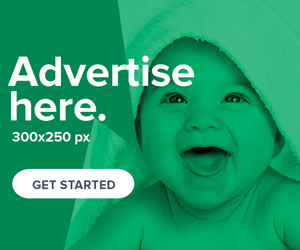

.jpeg)